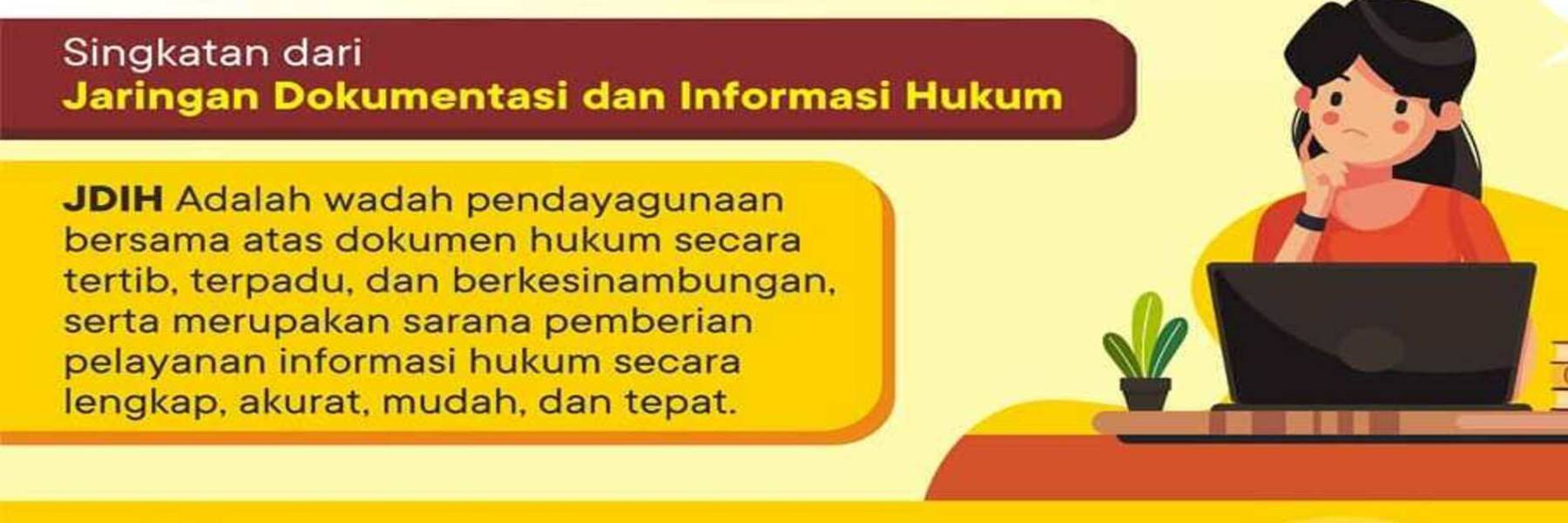Dengan adanya Putusan MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi
advokat, mereka kini dapat membantu masyarakat miskin dalam pendampingan
hukum, termasuk di pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu
memperkuat akses keadilan bagi masyarakat termarjinalkan.

Setiawan Jodi Fakhar. Foto: Istimewa
Ada kabar baik untuk
masyarakat yang kesulitan membayar jasa advokat saat menghadapi kasus
hukum. Kini, bantuan hukum dapat diperoleh secara gratis dari dosen PNS
yang mengajar di Fakultas Hukum baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan memenuhi syarat yang diatur
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat. Syarat tersebut
meliputi mengikuti Pendidikan Kekhususan Profesi Advokat (PKPA), lulus
Ujian Profesi Advokat (UPA), dan disumpah di Pengadilan Tinggi untuk
mendapatkan lisensi.
Keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) mempertegas hal tersebut melalui Putusan Nomor
150/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan
Pasal 20 ayat (2) UU Advokat dinyatakan tidak berlaku bagi dosen PNS
yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Artinya, dosen PNS kini
dapat menjalankan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi tanpa khawatir melanggar ketentuan hukum.
Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang
bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni. Memberikan bantuan hukum gratis adalah
bentuk nyata dari pengabdian ini.
Keputusan MK ini
membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang
mampu. Dengan bantuan hukum gratis dari dosen PNS, akses keadilan
menjadi lebih mudah. Dosen PNS juga dapat menerapkan ilmu hukum secara
langsung, memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan dalam sistem
hukum Indonesia. Namun, keputusan ini juga menimbulkan polemik di
kalangan advokat non-PNS, yang mempertanyakan independensi advokat di
bawah naungan pemerintah.
Polemik ini tidak
baru. Dalam jurnal yang ditulis Akhiar Salmi berjudul “Sumbangan
Pemikiran Terhadap RUU Advokat (2001)”, disebutkan bahwa membatasi dosen
PNS hanya pada pendampingan hukum non-litigasi dianggap tidak adil. Hal
ini dinilai diskriminatif, terutama jika dibandingkan dengan dokter PNS
yang diizinkan membuka praktik. Menurut Salmi, dosen yang berpraktik
sebagai advokat dapat membantu mahasiswa memadukan teori dan praktik
hukum.
Namun, ada perbedaan
mencolok antara advokat murni dan dosen PNS yang menjadi advokat. Dosen
PNS tetap mendapatkan gaji bulanan dari negara, dan di masa pensiun,
mereka berhak atas tunjangan pensiun. Sebaliknya, advokat murni harus
bergantung sepenuhnya pada pendapatan dari klien. Ketika klien sepi,
risiko menjadi “pengangguran banyak acara” pun tak terhindarkan.
Dengan adanya Putusan
MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat, mereka kini dapat
membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, termasuk di
pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat akses keadilan
bagi masyarakat termarjinalkan.
Profesi advokat
menuntut kesabaran ekstra, kemampuan mendengar, dan keteguhan hati.
Meski menghadapi banyak tantangan, advokat tetap harus profesional dalam
membantu pencari keadilan. Berbeda dengan dosen PNS yang memiliki
penghasilan tetap, advokat murni harus kreatif dan mandiri dalam mencari
sumber penghasilan tambahan. Oleh karena itu, advokat perlu menunjukkan
profesionalisme agar tetap relevan di tengah persaingan.
Membela Tanpa Pamrih: Advokat untuk Rakyat Termarjinalkan
Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,
dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU. Dalam Putusan MK,
perdebatan muncul terkait Pasal 3 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan
bahwa seseorang tidak boleh diangkat sebagai advokat jika masih
berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Sementara itu,
Pasal 20 UU Advokat melarang advokat menjalankan profesi lain yang dapat
mengurangi kebebasan atau merugikan profesi advokat.
Profesi advokat
dikenal sebagai officium nobile atau profesi mulia, setara dengan
penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun, dengan
diperbolehkannya dosen PNS menjadi advokat, muncul kekhawatiran akan
adanya dualisme peran. Meski begitu, dosen PNS hanya diperbolehkan
menangani klien secara cuma-cuma, sehingga tidak ada konflik kepentingan
terkait keuntungan finansial.
Bantuan hukum
cuma-cuma atau pro bono sendiri sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan
(2) UU Advokat. Sayangnya, dalam praktik, pelaksanaannya sering tidak
berjalan optimal. Banyak advokat yang enggan memberikan bantuan hukum
gratis, karena kebutuhan finansial yang mendesak. Akibatnya, masyarakat
miskin seringkali terpinggirkan dari akses keadilan.
Untuk menjawab masalah
ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
UU ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin akses keadilan bagi
masyarakat rentan. Bantuan hukum juga melibatkan paralegal, mahasiswa
hukum, serta dosen PNS dalam pendampingan hukum, baik secara litigasi
maupun non-litigasi.
Hak atas bantuan hukum
sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi yakni Undang-Undang No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang
berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam sistem
peradilan pidana Indonesia, Pasal 54 KUHAP juga mengatur bahwa tersangka
atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum di
setiap tingkat pemeriksaan.
Dengan adanya Putusan
MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat, mereka kini dapat
membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, termasuk di
pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat akses keadilan
bagi masyarakat termarjinalkan.
engan adanya Putusan
MK yang memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat, mereka kini dapat
membantu masyarakat miskin dalam pendampingan hukum, termasuk di
pengadilan. Keputusan ini diharapkan mampu memperkuat akses keadilan
bagi masyarakat termarjinalkan.
Semoga, ke depan tidak
ada lagi kasus seperti yang baru-baru ini viral: seorang pengacara
menipu Dwi Ayu Darmawanti, pegawai toko roti yang menjadi korban
penganiayaan bosnya di Cakung, Jakarta Timur. Untuk membayar pengacara,
Dwi Ayu bahkan terpaksa menjual motornya. Namun, pengacara tersebut
justru kabur setelah menerima uangnya. Kasus seperti ini tidak boleh
terulang.
Seperti yang pernah
dikatakan Pramoedya Ananta Toer: “Kalau ahli hukum tak merasa
tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu
jalanan.”
Oleh : Setiawan Jodi Fakhar, S.H., ( hukumonline.com )